21 Momentous Photographs You Should Not Miss!
For the very first time since the beginning of human history, a long exposure shot had been shot by Joseph Nicéphore Niépce.......
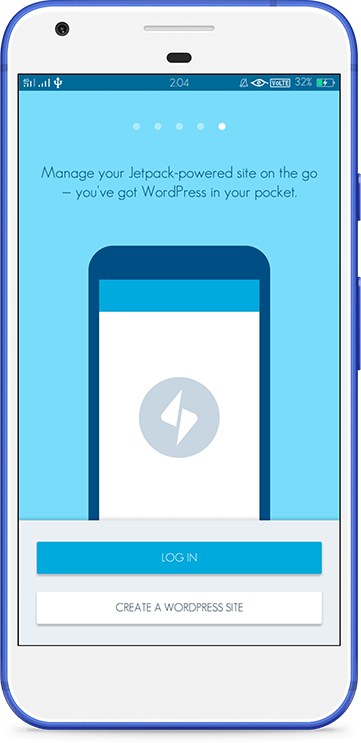
独家优惠奖金 100% 高达 1 BTC + 180 免费旋转
Subaltern dalam Pusaran Pandemi
Nasib ketiga orang yang saya ceritakan bisa jadi dialami oleh banyak orang di Indonesia. Mereka berada dalam posisi rentan. Mengakses apa yang disediakan negara saja rasanya susah. Selain disebabkan oleh faktor akses juga terkait tingkat pemahaman atau pendidikan. Mereka tidak paham kewajiban negara terhadap warganya. Alih-alih mau menuntut ke pemerintah, yang ada difikiran mereka adalah gimana mereka dapat hidup ditengah kondisi yang makin memburuk.
Sebulan lebih pandemi Covid-19 menjadi teror bagi kita semua. Banyak orang memutuskan mengurangi aktivitasnya di luar rumah, termasuk saya. Tetapi tidak sedikit pula orang yang memutuskan untuk tetap beraktivitas diluar rumah demi keberlangsungan hidup. Dalam sebuah kesempatan aksi sosial. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang yang terpaksa harus tetap bekerja di jalanan. Dari pembicaraan tersebut tulisan ini hadir.
Yang pertama, Pak Giman namanya. Sudah 14 tahun merantau ke Surabaya. Pria berusia 65 tahun ini mempunyai keluarga di Nganjuk. Pekerjaan sehari- hari adalah pengayuh becak di sebuah pasar di Surabaya. Setiap hari dia bergumul dengan panas dan debu jalanan. Pandemi kali ini membuat dia harus menghela nafas panjang karena pendapatannya berkurang drastis. Pak Giman adalah salah satu dari sekian orang yang tinggal di Surabaya tetapi secara administasi bukan warganya. Dia kerap kali tidak bisa mengakses program dan fasilitas dari pemerintah kota mengingat dia tidak ber-KTP Surabaya. Hal tersebut dia jalani selama bertahun-tahun karena tidak mungkin dia harus memboyong keluarganya ke Surabaya. 2 bulan sekali dia harus pulang ke rumah kecilnya di Nganjuk untuk menunaikan kewajibannya menafkahi istri dan anak-anaknya.
Beda lagi dengan Yessy, seorang waria yang biasanya mengamen di salah satu jalanan di Surabaya. Pendapatannya dari ngamen berkurang drastis karena mulai banyak warung-warung pinggir jalan yang sepi pengunjung. Selain itu juga dia juga mulai mengurangi aktifitasnya di jalanan. Karena rasa takut yang pasti juga dirasakan banyak orang. Yessy siang itu terpaksa keluar karena uang dikantongnya mulai menipis. Dengan gayanya dia bercerita susahnya menjadi waria. Dalam kondisi normal saja mereka kerap diusir, apalagi dalam kondisi begini. Kelompok waria adalah kelompok rentan yang kehadirannya kerap kali dipandang sebelah mata baik oleh masyarakat maupun negara. Prilaku diskriminatif dan pelecahan seringkali mereka dapatkan sehari-hari.
Yoyon, adalah seorang diffabel tuna daksa yang keseharianya berjualan koran di salah satu perempatan jalan utama di Surabaya. Wabah membuat pendapatannya berkurang tajam. Orang dijalan mulai enggan berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal karena kekuatiran dia tertular virus. Hal tersebut membuat korannya tidak banyak terjual. Sehari terjual 5 buah dia sudah senang sekali, itupun orang membeli bukan atas dasar kebutuhan tapi lebih banyak atas dasar belas kasihan.
Cerita-cerita diatas saya dapatkan dalam agenda beberapa hari yang lalu ketika bergerak memberikan bantuan sembako kepada mereka yang masih beraktifitas dijalan. Tentunya ribuan bahkan jutaan orang yang saat ini merasakan dampak dari pandemi ini. Mulai dari mulai dibatasinya aktivitasnya, gajinya tidak dibayarkan utuh bahkan terpaksa di-PHK dan persoalan lain yang membuat kehidupan meraka dalam aspek ekonomi mengalami masalah. Tetapi ketiga orang yang saya ceritakan diatas cenderung berbeda. Mereka mengalami apa yang saya sebut sebagai kelompok sosial subordinat, dalam tulisan ini saya sebut sebagai sub-altern.
Subaltern dan Peran Negara
Istilah subaltern dipopularkan oleh pemikir Italia, Antonio Gramsci. Menurutnya, istilah ini merujuk pada kelompok sosial subordinat, yakni kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subyek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa.(Reed, 2012). Dalam referensi yang lain Gayatri Spivak dalam esainya, Can Subaltern Speak, menjelaskan bahwa sub memiliki tiga karakteristik: Pertama adanya penekanan dan didalamnya bekerja suatu mekanisme pendiskriminasian. Kedua, ketidakmampuan untuk menyuarakan aspirasi atas ketertindasannya. Ketiga, kaum subaltern tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kondisinya, sehingga diperlukan kaum intelektual yang sering dianggap sebagai “wakil” kelompok subaltern (Morris, 2010).
Istilah ini saya pinjam untuk menggambarkan kondisi-kondisi ketiga orang diatas yang saya temui. Pak Giman yang aktivitasnya lebih banyak di Surabaya tetapi karena urusan administrasi dia lebih sering tidak mendapatkkan akses dan fasilitas atas persoalan yang dia hadapi. Wabah hari ini membuat dia berada pada posisi sangat rentan mengingat untuk hidup saja susah, apalagi berfikir terhindar dari virus. Nasib Yessy pun tidak kalah memilukan, dalam kehidupan normal saja dia sering mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat atau bahkan dari keluarga. Apalagi dalam kondisi begini. Yoyon pun juga demikian. Nasibnya tidak kalah buruk, pandemi menjadikan dia harus berjuang agar tetap bisa hidup.
Nasib ketiga orang yang saya ceritakan bisa jadi dialami oleh banyak orang di Indonesia. Mereka berada dalam posisi rentan. Mengakses apa yang disediakan negara saja rasanya susah. Selain disebabkan oleh faktor akses juga terkait tingkat pemahaman atau pendidikan. Mereka tidak paham kewajiban negara terhadap warganya. Alih-alih mau menuntut ke pemerintah, yang ada difikiran mereka adalah gimana mereka dapat hidup ditengah kondisi yang makin memburuk. Apa masih mungkin bagi mereka berharap pada para intelektual jika sementara para intelektual lebih banyak yang menjadi juru bicara negara. Andaipun dia bukan juru bicara negara, pasti mereka akan berfikir beratus-ratus kali untuk mengkritik negara. Mengingat makin kesini negara kita makin kejam pada pengkritik-pengkritiknya.
Gambaran diatas juga menegaskan selalu ada orang-orang yang dibungkam di berbagai belahan dunia, mereka absolut tidak punya suara dan tidak dapat berbicara. Mereka rentan dan tidak mampu menyuarakan apa yang mereka alami. Kondisi sruktur ekonomi-politik yang membuat mereka begitu. Ditengah kondisi begini, rasanya penting sekali menjadi mayoritas yang tidak bungkam. Saatnya menggerakkan energi kita untuk memberi perhatian kepada mereka agar tidak selalu menjadi sub-altern dan berada pada posisi paling dasar kerentanan dalam kondisi pandemi begini.
Dilema PSBB dan Mudik
Pandemi Covid-19 yang makin hari tidak membuat kondisi sosial-ekonomi makin baik membuat pemerintah mengeluarkan aturan. Aturan Pembatasan wilayah Berskala Besar (PSBB) bagi beberapa wilayah dan larangan mudik sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua hal tersebut akan menambah beban baru bagi Giman, Yessy dan Yoyon. Ketika PSBB diterapkan apakah Giman harus tetap bertahan di Surabaya. Toh umpama bertahan apakah dia mendapat subsidi dari pemerintah daerah setempat. Ketika dia harus mudik, ada larang dari pemerintah yang infonya bakal dikenakan sangsi. Atau mungkin, Giman ini masuk kategori harus pulang kampung seperti apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Apapun itu, bagi Giman pulang kampung atau mudik tanpa membawa uang adalah sesuatu hal yang benar-benar buruk, sementara ketika bertahan di Surabaya apa mungkin dia berharap atas keberlangsungan hidupnya pada pemerintah.
Beda lagi dengan Yessy dan Yoyon, keduanya kerap dianggap tidak sempurna di masyarakat. Orang-orang yang dalam kehidupan normal sudah harus berjuang keras dan pada saat wabah pun harus meningkatkan perjuangannya berlipat-lipat agar bisa hidup. Bagi mereka mungkin tidak mudik bukan persoalan, toh mereka juga orang asli Surabaya. Tetapi ketika ada PSBB diterapkan, apa kondisi mereka tidak semakin terjepit? Waktu yang akan menjawab hal tersebut. Subalternisasi akan selalu terjadi ketika perhatian negara hanya terfokus pada yang kaya (pemilik modal) dan menjadikan yang miskin makin termiskinkan oleh kebijakan-kebijakannya. Yang menindas semakin leluasa menindas, yang tertindas semakin tak bisa bersuara dalam penindasan yang semakin merajalela.
Sejujurnya saya agak pesimis berharap pada negara terkait kondisi dari tiga orang diatas yang sangat mungkin ada banyak orang yang bernasib seperti mereka. Tetapi akan merasa bersalah dan berdosa sekali jika hal tersebut tidak saya tulis dan ulas. Cuma itu saja motivasi saya menulis ini. Kenapa begitu, sebulan lebih ini kita dipertotonkan kejadian bagaimana negara gagap menghadapi kondisi ini. Dari persoalan inskonsistensi ucapan, ketidak- kompakan dan hal-hal konyol lainnya. Bagaimana mungkin suara sub-altern terdengar, wong kita-kita yang jelas-jelas nasibnya lebih beruntung dari ketiga orang diatas saja nasibnya juga penuh ketidak-pastian.
Related posts:
Lessons I Learned from Corona Pandemic
When I was thinking about this pandemic, I got lots of things in my mind and I realized that corona pandemic is trying to teach us some lessons. Now I also learned somethings from the pandemic. China…
Sadhguru
Painful to learn about the deaths of five of our men in uniform. Nation cannot afford to lose young uniformed men to senseless violence. Urgent need to rid the world of the scourge of terrorism. –Sg…